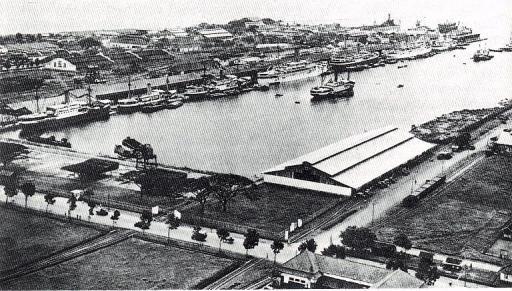PARADIGMA PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Oleh : Empi Muslion.JB
===============================
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara, dalam waktu relatif singkat (1999-2002), telah mengalami 4 (empat) kali perubahan. Dengan berlakunya amandemen UUD 1945 tersebut, telah terjadi perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu : (1) penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); (2) ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional; dan (3) diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mengenai dokumen perencanaan pembangunan nasional yang selama ini dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan adalah dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Ketetapan MPR ini menjadi landasan hukum bagi Presiden untuk dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan dengan memperhatikan saran DPR, sekarang tidak ada lagi.
Instrumen dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai acuan utama dalam memformat dan menata sebuah bangsa, mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Perubahan mendasar yang terjadi adalah semenjak bergulirnya bola reformasi, seperti dilakukannya amandemen UUD 1945, demokratisasi yang melahirkan penguatan desentralisasi dan otonomi daerah (UU Nomor 22/1999 dan UU Nomor 25/1999 yang telah diganti dengan UU Nomor 32/2004 dan UU Nomor 33/2004), UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, penguatan prinsip-prinsip Good Governance : transparansi, akuntabilitas, partisipasi, bebas KKN, pelayanan publik yang lebih baik. Disamping itu dokumen perencanaan pembangunan nasional juga dipengaruhi oleh desakan gelombang globalisasi (AFTA, WTO, dsb) dan perubahan peta geopolitik dunia pasca tragedi 11 September 2001.
Perjalanan dokumen perencanaan pembangunan nasional sebagai kompas pembangunan sebuah bangsa, perkembangannya secara garis besar dapat dilihat dalam beberapa periode yakni :
Dokumen perencanaan periode 1958-1967
Pada masa pemerintahan presiden Soekarno (Orde Lama) antara tahun 1959-1967, MPR Sementara (MPRS) menetapkan sedikitnya tiga ketetapan yang menjadi dasar perencanaan nasional yaitu TAP MPRS No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara, TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969, dan Ketetapan MPRS No.IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.
Dokumen perencanaan periode 1968-1998
Landasan bagi perencanaan pembangunan nasional periode 1968-1998 adalah ketetapan MPR dalam bentuk GBHN. GBHN menjadi landasan hukum perencanaan pembangunan bagi presiden untuk menjabarkannya dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita), proses penyusunannya sangat sentralistik dan bersifat Top-Down, adapun lembaga pembuat perencanaan sangat didominasi oleh pemerintah pusat dan bersifat ekslusif. Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai subjek utama out-put perencanaan kurang dilibatkan secara aktif. Perencanaan dibuat secara seragam, daerah harus mengacu kepada perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat walaupun banyak kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan di daerah. Akibatnya mematikan inovasi dan kreatifitas daerah dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya. Distribusi anggaran negara ibarat piramida terbalik, sedangkan komposisi masyarakat sebagai penikmat anggaran adalah piramida seutuhnya.
Sebenarnya pola perencanaan melalui pendekatan sentralistik/top-down diawal membangun sebuah bangsa adalah sesuatu hal yang sangat baik, namun pola sentralistik tersebut terlambat untuk direposisi walaupun semangat perubahan dan otonomi daerah telah ada jauh sebelum dinamika reformasi terjadi.
Dokumen perencanaan periode 1998-2000
Pada periode ini yang melahirkan perubahan dramatis dan strategis dalam perjalanan bagsa Indonesia yang disebut dengan momentum reformasi, juga membawa konsekuensi besar dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan nasional, sehingga di periode ini boleh dikatakan tidak ada dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dapat dijadikan pegangan dalam pembangunan bangsa, bahkan sewaktu pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid terbersit wacana dan isu menyangkut pembubaran lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional, karena diasumsikan lembaga tersebut tidak efisien dan efektif lagi dalam konteks reformasi.
Dokumen perencanaan periode 2000-2004
Pada sidang umum tahun 1999, MPR mengesahkan Ketetapan No.IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Berbeda dengan GBHN-GBHN sebelumnya, pada GBHN tahun 1999-2004 ini MPR menugaskan Presiden dan DPR untuk bersama-sama menjabarkannya dalam bentuk Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat APBN, sebagai realisasi ketetapan tersebut, Presiden dan DPR bersama-sama membentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004. Propenas menjadi acuan bagi penyusunan rencana pembangunan tahunan (Repeta), yang ditetapkan tiap tahunnya sebagai bagian Undang-Undang tentang APBN. sedangkan Propeda menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada).
Dokumen perencanaan terkini menurut UU Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN
Diujung pemerintahannya Presiden Megawati Soekarno Putri menandatangani suatu UU yang cukup strategis dalam penataan perjalanan sebuah bangsa untuk menatap masa depannya yakni UU nomor 25 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional. Dan bagaimanapun UU ini akan menjadi landasan hukum dan acuan utama bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memformulasi dan mengaplikasikan sesuai dengan amanat UU tersebut. UU ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam UU ini pada ruang lingkupnya disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.
Intinya dokumen perencanaan pembangunan nasional yang terdiri dari atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenanganya mencakup : (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan periode 20 (dua puluh) tahun, (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan periode 5 (lima) tahun, dan (3) Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP dan RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.
Lahirnya UU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini, paling tidak memperlihatkan kepada kita bahwa dengan UU ini dapat memberikan kejelasan hukum dan arah tindak dalam proses perumusan perencanaan pembangunan nasional kedepan, karena sejak bangsa ini merdeka, baru kali ini UU tentang perencanaan pembangunan nasional ditetapkan lewat UU, padahal peran dan fungsi lembaga pembuat perencanaan pembangunan selama ini baik di pusat maupun di daerah sangat besar.
Tapi pertanyaan kita, apakah UU nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN ini tidak hanya bertukar kulit saja ? apakah RPJP, RPJM, RKP itu secara model dan mekanisme perumusannya sama saja halnya dengan program jangka panjang yang terkenal dengan motto menuju Indonesia tinggal landas, Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dengan berbagai periode dan APBN sebagai program satu tahunnya semasa pemerintahan Orde Baru ?
Apakah aspirasi, partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam proses penjaringan, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi dari perencanaan yang dibuat, masih dihadapkan pada balutan sloganistis dan pemenuhan azas formalitas belaka ? mungkin substansi ini yang perlu kita sikapi bersama dalam konteks perumusan kebijakan dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun daerah ini kedepan.
Catatan : Sudah pernah dipublikasikan pada Koran Kaba Luhan Nan Tuo
Semoga Bermanfaat